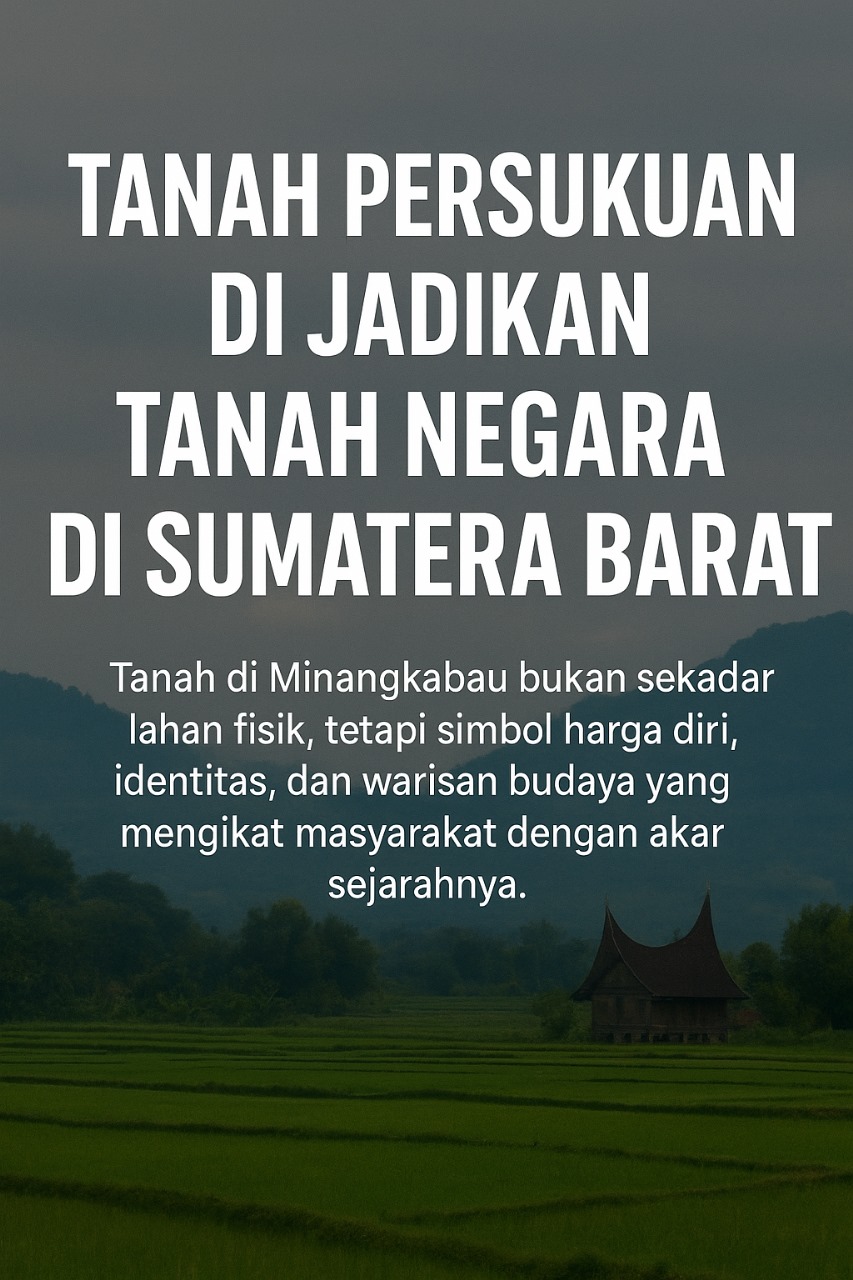
Tanah Ulayat di Persimpangan: Adat yang Tergusur oleh Negara
Di ranah Minangkabau, tanah bukan sekadar hamparan bumi tempat berpijak, melainkan sumber identitas dan marwah kaum. “Pusako tinggi indak buliah dijua, indak buliah digadai” — begitu pituah adat menegaskan sakralitas tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang tidak boleh berpindah tangan kepada pihak luar. Namun, di tengah derasnya arus pembangunan dan kebijakan negara, makna suci itu kini terdesak ke tepi. Tanah ulayat, yang dahulu menjadi simbol kedaulatan adat, kini sering kali berujung menjadi tanah negara.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di satu nagari, melainkan di banyak wilayah Sumatera Barat. Dengan alasan pembangunan infrastruktur, program reforma agraria, atau sertifikasi lahan, negara melalui instrumen hukum positifnya perlahan-lahan “merasionalisasi” tanah ulayat. Proses administrasi ini sering kali tidak memerhatikan struktur sosial adat, yang justru menjadi akar kuat kehidupan masyarakat Minangkabau.
Masalahnya bukan pada pembangunan, melainkan pada cara negara memandang tanah. Dalam kacamata hukum nasional, tanah adalah objek ekonomi yang dapat dikuasai, disertifikasi, bahkan dialihkan. Sementara dalam adat, tanah adalah simbol keberlanjutan hidup dan kesatuan kaum—bukan milik perseorangan, tetapi milik bersama yang dijaga turun-temurun.
Konflik antara adat dan negara muncul ketika logika kepemilikan berubah menjadi logika penguasaan. Ketika tanah ulayat disertifikasi menjadi hak milik individu atau dikuasai untuk kepentingan umum, yang hilang bukan hanya sebidang lahan, melainkan seluruh sistem nilai yang melingkupinya. Hubungan sosial, tanggung jawab kaum, dan identitas adat terkikis sedikit demi sedikit.
Ironisnya, banyak masyarakat adat yang kini berada dalam posisi lemah karena minim pemahaman hukum dan tekanan ekonomi. Di satu sisi, mereka ingin mempertahankan tanah ulayat; di sisi lain, desakan ekonomi dan kebutuhan hidup mendorong mereka untuk melepasnya. Dalam kondisi seperti itu, negara semestinya hadir bukan sebagai penggusur, tetapi sebagai pelindung yang memahami nilai-nilai lokal.
Solusi yang ideal bukan sekadar pengakuan simbolik atas tanah ulayat, melainkan integrasi nyata antara hukum adat dan hukum negara. Pemerintah daerah dan lembaga adat perlu bersinergi memastikan agar tanah ulayat tetap berada di bawah penguasaan masyarakat hukum adat, dengan batas yang jelas dan perlindungan hukum yang kuat.
Jika tanah ulayat hilang dari tangan anak nagari, maka yang hilang bukan hanya hak kepemilikan, tetapi juga sejarah, budaya, dan marwah sebuah bangsa. Adat Minangkabau akan kehilangan pijakan jika pusaka tinggi sudah menjadi angka dalam sertifikat tanah negara.
Kini, pertanyaannya tinggal satu: apakah kita akan terus membiarkan tanah ulayat — simbol jati diri Minangkabau — tergusur perlahan oleh kekuasaan negara? Atau kita akan berdiri menjaga warisan leluhur ini agar tetap menjadi milik bersama, bukan milik yang dikuasai?




0 Komentar